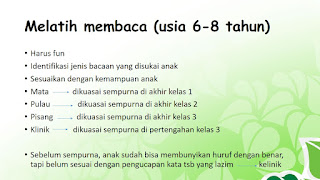Sabtu, 26 November 2016
Jumat, 09 September 2016
Minggu, 04 September 2016
Senin, 11 Juli 2016
Rintisan Buku Pelatihan Membaca Berbasis Penelitian Psikolinguistik: Mahir Membaca 1
Harwintha Y. Anjarningsih sudah menjadi dosen di program studi Inggris, Fakultas Ilmu
Budaya, Universitas Indonesia sejak lulus program sarjana pada tahun 2003.
Memfokuskan diri pada studi psiko- dan neurolinguistik, dia sangat tertarik
pada isu-isu pemrosesan bahasa dan masalah bahasa baik pada anak-anak maupun
orang dewasa. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya pada bidang
afasiologi di Rijksuniversiteit Groningen, Belanda, Harwintha kembali ke
Indonesia dan menekuni riset dan publikasi di bidang gangguan bahasa.
Ketertarikan kepada pendidikan berkebutuhan khusus sudah dimilikinya sejak
menyelesaikan disertasi mengenai tes skrining untuk disleksia perkembangan pada
tahun 2006. Buku tulisannya adalah Jangan Kucilkan Aku karena Aku tidak Bisa
Membaca: Pentingnya Identifikasi Dini Disleksia untuk Masa Depan Anak (2011)
dan Otak dan Kemampuan Berbahasa (2011). Harwintha dapat
dikontak di alamat email wintha_salyo@yahoo.com dan nomor telpon seluler 0812
860 60 584. Kumpulan tulisannya bisa diakses di harwintha.blogspot.com.
Materi latihan membaca di dalam buku
ini disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian oleh Grup Psikolinguistik, Laboratorium
Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia yang
dikembangkan oleh penulis dan para mahasiswanya. Sebagian besar kata-kata di
dalam Mahir Membaca 1 adalah kata dengan dua suku kata yang merupakan kata-kata
yang sangat sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Urutan materi
latihan membaca diatur berdasarkan bangun suku kata yang lebih mudah untuk
dikuasai oleh para pembaca pemula: kata sederhana (mis. bola), kata dengan diftong (mis. pulau), kata dengan digraf (mis. jagung), dan kata dengan gugus konsonan (mis. planet). Disarankan untuk
membaca materi latihan secara berurutan (sederhana-diftong-digraf-gugus
konsonan) dan pindah setelah tercapai akurasi minimal sebesar 75%. Jika orang
tua atau guru ingin memberikan kata-kata lainnya, disarankan untuk memilih
kata-kata dengan dua atau tiga suku kata dan bangun suku kata yang sesuai
dengan materi yang sedang dibaca. Dengan kata lain, jika anak sedang berlatih
dengan kata sederhana, jangan terlalu banyak melatihkan diftong atau digraf
dulu. Kuatkanlah pemahaman anak atas kata-kata dengan susunan Konsonan-Vokal-Konsonan-Vokal
terlebih dulu.
Penguasaan dengan akurasi minimal 90%
atas materi membaca di Mahir Membaca 1 dan kata-kata dengan bangun suku kata
sejenis lazimnya tercapai di akhir kelas 2 atau pertengahan kelas 3 Sekolah
Dasar. Jika di akhir kelas 3 anak masih mengalami kesulitan yang besar, orang
tua atau guru dapat mengecek lebih lanjut apakah ada kesulitan belajar, atau
gangguan belajar dengan menghubungi ahli bahasa anak, ahli gangguan bahasa,
psikolog anak, atau dokter spesialis anak. Dengan demikian, anak dapat diberi
perhatian khusus yang sesuai dengan gaya belajarnya dengan tujuan untuk
menguasai kemahiran membaca yang sangat penting untuk keberhasilan
pendidikannya.
Kami ucapkan selamat berlatih.
Depok,
11 Juli 2016,
Harwintha
Y. Anjarningsih, PhD
Kamis, 17 Maret 2016
Makalah Harwintha untuk KOLITA 14, 2016
http://adl.aptik.or.id/default.aspx?tabID=61&id=168146&src=a
Characterising the Reading Development of Indonesian Children
Harwintha Y. Anjarningsih
Linguistics Department, Faculty of Humanities,
Universitas Indonesia
wintha_salyo@yahoo.com
To
characterise the reading development of Indonesian children, a tool is
currently developed. The tool builds on two important findings from previous
literature: that the depth of a language’s orthography influences reading
development (e.g., Seymore, Aro, & Erskine, 2003); and that
reading development proceeds in phases (e.g., Ehri, 2005). In
languages with deep orthography such as English, reading is made challenging by
irregular words, such as ‘pint,’ which cannot be decoded successfully just by
relying on phonological strategy. It does not work when children try to
assemble the words based on the Grapheme-Phoneme Conversion that can be found
in regular words, such as ‘mint.’ Furthermore,
in English, each grapheme or series of graphemes can be read differently
in different words. For example, the graphemes <c>
and <h> can be
read as /ʃ/ in the word ‘moustache,’ /t ʃ/ in the word ‘chair,’ and /k/ in the
word ‘choir.’ The work of Seymour, Aro, &
Erskine (2003)
shows that children reading English are not reading fluently about 50% of
familiar words by the end of the first school year. On the other hand, in languages with
transparent orthographies, such as Italian, children have become accurate and
fluent in reading simple, familiar words by the end of the first school year.
In terms of orthography, Indonesian is transparent, much like Italian. It is
interesting to ask how children’s reading proceeds in such a transparent
orthography which has not been extensively investigated. In this research
project, a tool that makes use of several variables of the written Indonesian
words is developed and tested to uncover its suitability and reliability for
nationwide application. One hundred disyllabic, frequent words (10,000 most
frequent words based on the IndonesianWac corpus) are read by the participants
and divided into four groups: (1) simple words; (2) words with diphthongs ; (3)
words with digraphs; and (4) words with consonant clusters. Two groups of
normally developing children have been tested: 16 pre-school children (mean
age=5 years; 7 months); 17 grade 1 children (mean age=7 years).
Answers are recorded digitally and written on answer sheets. Overall, by
keeping number of syllables constant, it is possible to assess how syllable
structure(s) affects the children’s reading development and how chronological
age affects reading development. Our
preliminary findings are: (1) at the pre-school stage, (a) all four groups of
words are difficult, (b) reading mistakes predominantly show visual
errors which still show 50% of the graphemes in the target
words,
and (c) digraphs and consonant clusters presented the most difficult challege
as evidenced by the percentages of mistakes made; (2) at the grade one level,
(a) simple words and words with diphthongs are less difficult to read, (b)
mistakes are also predominantly visual
, although to a much smaller extent than that of the
pre-schoolers, and
(c) digraphs and consonant clusters still present the most difficult challenge
at this level.
Reading Acquisition Reading
Development Reading
Disabilities Dyslexia
Minggu, 22 November 2015
Rintisan Pemetaan Milestones Performa Membaca pada anak-anak Indonesia (Seminar Volunteer Educators Network, 21 Nov 2015)
Disleksia
perkembangan (developmental dyslexia)
adalah sebuah kondisi kesulitan belajar yang termanifestasi secara perilaku dengan
kesulitan untuk belajar membaca dan untuk menjadi pembaca yang mahir. Menurut
teori fonologis (phonological theory of
dyslexia), disleksia terjadi oleh karena adanya gangguan (impairment) di representasi kognitif
dari bunyi-bunyi bahasa di benak seseorang (Stanovich, 1988 dan Snowling, 2000
dalam White, Milne,
Hansen, Swettenham, Frith, dan Ramus, 2006). Kondisi seperti ini akan mengganggu
kemahiran dalam memetakan grafem (huruf) dan bunyi-bunyi bahasa. Sebagai
contoh, ketika kita membaca kata SAMA, kita harus memetakan bahwa grafem
sederhana S mewakili bunyi fonem /s/, grafem sederhana A mewakili bunyi fonem
/a/, dan grafem sederhana M mewakili bunyi fonem /m/. Pemetaan ini akan menjadi
lebih kompleks untuk digraf (NG, NY, KH, SY) dan diftong (AI, AU, OI) karena
dua grafem atau dua huruf dipetakan kepada satu bunyi.
Identifikasi
disleksia perkembangan di Indonesia masih sangat menantang dikarenakan oleh
paling tidak dua hal. Pertama, ketiadaan tes-tes membaca yang ternorma dan
terstandarisasi untuk dapat menilai performa membaca anak-anak. Idealnya, diagnosis
disleksia ditegakkan setelah ada bukti yang valid bahwa performa membaca
seorang anak ada di 1 Deviasi Standar di bawah rata-rata nilai akurasi membaca di
dalam nilai performa yang sudah dinormakan (Sprenger-Charolles, Colé, Lacert,
Serniclaes, 2000) sehingga dapat ditunjukkan bahwa dia memiliki performa yang
jauh berada di bawah performa yang lazim menurut IQ, pengalaman sekolah, dan
usia kronologis. Dengan adanya tes-tes ini, performa membaca anak akan dapat
dilihat secara jelas pada berbagai jenis kata yang diatur berdasarkan
bunyi-bunyi bahasa yang menyusunnya, bangun suku kata, jumlah suku kata, dan
lain sebagainya. Hal kedua yang membuat identifikasi
disleksia perkembangan masih sangat menantang di Indonesia adalah ketiadaan
pemetaan performa membaca (reading
milestones atau reading development)
anak-anak Indonesia, dengan memperhitungkan usia kronologis, jenis-jenis dan
kompleksitas kata, dan variabel-variabel lain seperti bahasa ibu, kondisi
diglosia bahasa Indonesia (Bahasa Indonesia dianggap lebih tinggi prestisenya
dibanding dengan bahasa daerah) dan status sosio-ekonomi. Dengan ketiadaan ini,
sering kali kita tidak bisa menjawab pertanyaan “Apakah lazim anak saya atau
murid saya pada usia sekian atau kelas sekian masih kesulitan membaca?” Tidak
mudah dijawab karena kita belum tahu bagaimana proses belajar membaca yang
lazim. Sebagai sebuah rintisan, makalah ini akan memaparkan temuan-temuan awal
dari penelitian antar-universitas mengenai pemetaan performa membaca pada
anak-anak Indonesia, baik yang berkembang dengan lazim atau yang sudah
mengalami kesulitan membaca di sekolah. Data berasal dari penelitian-penelitian
yang dilakukan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,
Depok dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya.

Di mana:
S = Deviasi Standard
Σ = jumlah dari
X = nilai individual
M = nilai rata-rata dan n = jumlah sampel (jumlah nilai)
Σ = jumlah dari
X = nilai individual
M = nilai rata-rata dan n = jumlah sampel (jumlah nilai)
Rumus
penghitungan Deviasi Standar (dikutip dari Anjarningsih, 2011, hlm. 11)
Pada
sebuah penelitian yang sedang berjalan, Windiani Putri, Anjarningsih, dan
Suhardijanto melihat performa membaca oleh anak-anak usia prasekolah (rata-rata
5 tahun 8 bulan) di sebuah lembaga kursus membaca di pinggiran Jakarta. Ada dua
kelompok, yaitu kelompok A yang memulai kursus di tahun 2014 (durasi rata-rata
1 tahun 3 bulan, rentang 10 bulan-22 bulan), dan kelompok B yang memulai kursus
di tahun 2015 (durasi kursus rata-rata 4 bulan, rentang 1 bulan-9 bulan). Kedua
kelompok diminta membaca 100 kata-kata dwisilabik (mengandung dua suku kata)
yang dimanipulasi bangun suku katanya. Pada jenis pertama, 25 kata-kata
dwisilabik yang dibaca mempunyai bangun suku kata yang sederhana.
Pada
kelompok A (durasi kursus rata-rata 1 tahun 3 bulan), ketika membaca jenis kata
sederhana kesalahan-kesalahan yang ditemukan adalah kesalahan pengubahan,
penghilangan, penambahan, visual, dan substitusi. Total ada 66 kesalahan dari
400 kata hasil bacaan (16,5 %).
A.
Pengubahan
bagi à
/ba.yi/ /ba.di/
bila
à
/ba.la/ /bi.ba/
cara
à
/ca.la/ /ca.ri/
dari
à
/da.li/ /ba.ri/
data à
/ba.ya/
B.
Penghilangan
guru
à
/ru/
C.
Penambahan
maka
à
/ma.kan/
kota
à
/ko.tak/
tahu
à
/ta.hun/
muda
à
/mu.dah/
bila
à
/bi.lam/
D.
Visual
bagi
à
/ba.ca/
hari
à
/ha.ya/
E.
Substitusi
juga
à
/do.a/
Pada
kelompok B (durasi kursus rata-rata 4 bulan), jenis-jenis kesalahan baca yang dilakukan
adalah kesalahan pengubahan, penghilangan, pembalikan, visual, dan substitusi. Ada
117 kesalahan dari 400 kata hasil bacaan (29,25 %).
A.
Pengubahan
demi
/de.mi/
cara
/ba.ra/
dari
/ba.ri/,
data
/ba.ta/
guru
/bu.ru/
B.
Penghilangan
pula
à
/pu.a/
muda
à
/u.da/
bagi
à
/ba/
juga
à
/ju/
guru
à
/ru/
kota
à
/tak/
C.
Pembalikan
nama
à
/ma.na/
D.
Visual
bagi
à
/bi.ji/
demi
à
/be.mi/
demi
à
/da.ma/
kota
à
/ka.o/
E.
Substitusi
demi
à
/ba.li/ /de.na/ /ma.da/
dulu
à
/la.ut/
juga
à
/bi.ba/
juta
à
/ja.wu/
nama
à
/men.da/ /nu.pah/
tahu
à
/ka.wu/
Berdasarkan
paparan di atas, terlihat bahwa akurasi pemetaan antara fonem (bunyi) dan
grafem (huruf) meningkat seiring dengan bertambahnya durasi belajar. Namun
demikian, setelah satu tahun pun, akurasi dalam membaca kata-kata dwisilabik
dengan bangun kata sederhana belum sempurna. Kemudian, perlu diingat juga bahwa
para peserta dalam penelitian ini berusia kronologis di bawah 7 tahun yang
merupakan usia minimal masuk sekolah di sekolah dasar negeri.
Anjarningsih
(2006) meneliti performa membaca anak-anak di awal kelas 3 SD (usia rata-rata 8
tahun 3 bulan). Ada beberapa hal yang menarik di performa kelompok yang
mendapatkan nilai akurasi membaca paling rendah (78,2 % berusia 8 tahun 11
bulan dan 74,56 % berusia 8 tahun 1 bulan). Di bawah ini adalah beberapa contoh
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kelompok ini:
A.
Regularisasi
kunyah
à
/ku.yah/
syura
à
/sa.yur/
syak
à
/sa.in/
B.
Substitusi
kalung
à
/ke.lu.ar.ga/
bunga
à
/bu.a.ya/
C.
Visual
skrup
à
/rup/
Kesalahan
regularisasi menunjukkan kesulitan dengan digraph NY dan SY. Kesalahan visual
juga menunjukkan kesulitan yang serupa, yaitu memproses klaster atau kumpulan
bunyi konsonan, yaitu SK. Dari yang seharusnya memproduksi tiga bunyi bahasa
atau fonem, yaitu /s/, /k/, dan /r/, hanya satu bunyi yang diproduksi, yaitu
/r/. Sangat menarik untuk mengamati kesalahan substitusi yang ada, yaitu
pembacaan kata-kata KALUNG, dan BUNGA sebagai KELUARGA dan BUAYA. Ini
menunjukkan bahwa selain adanya kesulitan dengan digraf, terlihat juga adanya
kerentanan terhadap pengaruh dari kata-kata lain di dalam leksikon anak-anak
ini. Ketika mereka kesulitan dengan grafem sederhana dan digraf, mereka mencari
kata apa di dalam leksikon mereka yang mereka anggap mirip dengan kata yang dibaca
dan kemudian menyebutkan kata yang mirip tersebut.
Juga
menarik untuk dilihat bahwa anak-anak pada Anjarningsih (2006) sudah belajar
membaca paling sedikit selama 2 tahun di sekolah dasar. Bahkan setelah 2 tahun,
masih terdapat kesulitan pemetaan fonem ke grafem yang mempengaruhi akurasi
membaca mereka. Saya memiliki keyakinan bahwa jika kesulitan-kesulitan yang
ditemui oleh Anjarningsih (2006) dan Windiani Putri, Anjarningsih, dan
Suhardijanto (belum terbit) masih ditemui pada kelas 3 di awal semester kedua
dan mengganggu performa akademik anak secara signifikan di sekolah, kita perlu
mencurigai adanya disleksia atau kesulitan membaca spesifik.
Kirana
(2011) merupakan salah satu dari sedikit skripsi yang membahas performa membaca
anak yang memang sudah mengalami kesulitan membaca di sekolah. Metode yang
digunakan salah satunya adalah melihat pola-pola kesalahan dalam membaca
kata-kata dalam teks-teks bacaan yang ada di buku sekolah responden penelitian
yang ketika itu berusia 11 tahun. Pola kesalahan yang ditemukan adalah beserta
beberapa contoh adalah:
A.
Penambahan
fonem
kesenian
à
/ke.se.ni.man/
pencegahan
à
/pən.cəŋ.ga.han/
kronis
à
/ko.ro.nis/
B.
Penambahan
suku kata
penjajah
à
/pən.ja.jah.an/
keberanian
à
/kə.bə..ra.ni.an.ña/
C.
Penghilangan
fonem
andil
à
/a.dil/
sarana
à
/sa.ran/
pendapa
à
/pə.da.pa/
D.
Pembalikan
pada
à
/da.pa/
alun-alun
à
/la.un.la.un/
bawah
à
/wa.bah/
E.
Kombinasi
dari
à
/da.rah/
masuk
à
/mak.sud/
organ
à
/o.raŋ/
Jika
kita tertarik untuk mengetahui mengapa semua kesalahan ini dapat terjadi, the phonological theory of dyslexia
dapat kita rujuk untuk memberikan penjelasan. Sama dengan yang sudah ditemukan
di bahasa-bahasa lain, kemahiran membaca di bahasa Indonesia dilandasi dengan
kesadaran fonologis bahwa kata-kata yang sudah diketahui para pembaca pemula
semenjak mereka balita dapat dipetakan kepada huruf-huruf dan suku kata ketika
ketika membaca. Gangguan dalam kesadaran fonologis ini dapat menyebabkan
gangguan di dalam proses belajar membaca, yang dapat menyebabkan semua
kesalahan yang sudah dipetakan di atas. Dengan memperhitungkan usia kronologis
dan tahapan membaca, diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan
mempunyai panduan dalam melakukan diagnosa disleksia. Kesalahan apa yang lazim
diproduksi pada tahun pertama belajar membaca pada usia 6-7 tahun, misalnya,
kemungkinan menjadi pertanda disleksia jika ditemukan pada anak berusia 8,5
tahun yang sudah belajar membaca selama 2 tahun lebih.
Anjarningsih
saat ini sedang melakukan penelitian intervensi dengan peserta seorang anak
usia 10 tahun dengan kesulitan membaca. Assessment
awal menunjukkan responden masih mengeja apa yang dibaca dan mengalami
kesulitan merangkai kata-kata yang mengandung digraf dan diftong, serta suku
kata tertutup atau Konsonan Vokal Konsonan (misalnya maKAN). Langkah intervensi
pertama adalah belajar menghitung jumlah suku kata (2 atau 3 suku kata per
kata) dan menghitung jumlah bunyi bahasa di dalam setiap suku kata. Jumlah suku
kata dihitung dengan tepukan dan jumlah bunyi bahasa dihitung dengan menaruh
sebuah bola kecil play doh, satu untuk setiap bunyi bahasa. Salah satu temuan
awal berkenaan dengan kesadaran fonologis adalah bahwa mengenali jumlah suku
kata relatif lebih mudah dibanding dengan mengenali jumlah bunyi bahasa
(sejalan dengan temuan Treiman, 1985), terutama mengenali konsonan kedua di
dalam sebuah suku kata tertutup. Misalnya, suku kata KAN dikatakan hanya
memiliki 2 bunyi bahasa yaitu /k/ dan /a/. Dengan demikian, bisa dikatakan
bahwa apa yang tidak dibaca oleh anak yang menjadi responden ini adalah bunyi
bahasa yang tidak disadari keberadaannya. Tugas seperti mengenali suku kata,
membalik urutan suku kata, menghilangkan suku kata, dan tugas-tugas serupa pada
tataran bunyi bahasa atau fonem bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas
kognitif kepada satuan-satuan bahasa ini yang pada waktunya akan memudahkan
pemahaman kepada pemetaan fonem dan grafem.
Paparan
di dalam makalah singkat ini merupakan rintisan untuk dapat membuat pemetaan
perkembangan kemampuan membaca anak-anak Indonesia. Kontribusi lembaga-lembaga
dan peneliti-peneliti lain sangat diharapkan untuk dapat membuat gambaran yang
utuh di dalam pemetaan ini mengingat bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku
bangsa, provinsi, bahasa daerah, dan variasi kondisi sosio-ekonomi yang sangat
berpengaruh kepada performa membaca anak, pada khususnya dan performa akademis
pada umumnya. Kontak dapat ditujukan ke nomor telpon seluler 0812 860 60 584 (sms
/ wa / telpon), pin BB 57A88D0C, dan alamat surat elektronik wintha_salyo@yahoo.com.
Daftar
Pustaka
Anjarningsih,
H.Y. (2006). Developmental Dyslexia
in Bahasa Indonesia: Developing a Screening Test. Tesis magister
Universitas Potsdam, Jerman.
Anjarningsih,
H.Y. (2011). Jangan Kucilkan Aku karena
Aku Tidak Mahir Membaca: Pentingnya Identifikasi Dini Disleksia untuk Masa
Depan Anak. Pustaka Cendekia Press: Yogyakarta
Kirana,
A. W. (2011). The Phonological Operation
that Happens during the Reading Activity Of A Child Aged 11 Years Old with
Dyslexia. Skripsi sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
Sprenger-Charolles,
L., Colé, P., Lacert, P., & Serniclaes, W. (2000). On subtypes of
developmental dyslexia: Evidence from processing time and accuracy score, di Canadian Journal of Experimental Psychology,
Vol. 54, No. 2, hlm. 87-103.
Treiman, R. (1985).
Onsets and rimes as units of spoken syllables: Evidence from children, di Journal
of Experimental Child Psychology, Vol. 39, hlm. 261-181.
White,
S., Milne, E., Rosen, S., Hansen, P., Swettenham, J., Frith, U., & Ramus,
F. (2006) The role of sensorimotor impairments in dyslexia: a multiple case
study of dyslexic children, di Developmental Science, Vol. 9,
No. 3, hlm. 237–269.
Windiani Putri, A.
Anjarningsih, H.Y., Suhardijanto, T. (belum terbit). Pengaruh
Digraf, Diftong, dan Gugus Konsonan Terhadap Performa Membaca oleh Anak.
Skripsi sarjana, Universitas Indonesia, Depok.
Langganan:
Postingan (Atom)